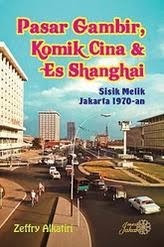 Judul buku: Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-an
Judul buku: Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-anPenulis: Zaffry Alkatiri
Penerbit: Masup Jakarta - Komunitas Bambu
Tebal: x + 190 hlm
KOTA bukan sekadar lanskap geografis. Kota adalah wajah masyarakat yang menempatinya. Keberadaan dan perkembangannya adalah representasi dari eksistensi dan pergulatan hidup masyarakatnya. Memahami sejarah sebuah kota senantiasa akan membawa kita pada pemahaman kompleksitas kehidupan dalam suatu ruang. Dari kehidupan sosial, ekonomi, bahasa, budaya, sampai tradisi lokal yang telah turun-temurun.
Buku Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-an, mencoba merekam kehidupan warga kota Jakarta dengan segala kompleksitas dan kemajemukannya. Dengan membatasi lingkup waktu hanya sekitar tahun 1970-an, penulis rupanya ingin memotret dinamika awal modernisasi kota Jakarta.
Pada 1970-an, para pemangku kepentingan yang sangat berkepentingan atas pembangunan kota Jakarta memang berupaya membentuk identitas Jakarta. Pada 1970-an dinyatakan Jakarta tidak akan berkembang menjadi kota metropolitan seperti yang digembar-gemborkan pemerintahnya. Jakarta akan tetap menjadi sebuah perkampungan besar, dengan segala persoalannya yang rumit. Kala itu, Ali Sadikin, gubernur Jakarta, juga pernah menyatakan bahwa Jakarta kota tertutup bagi pendatang. Hal ini diungkapkannya akibat laju perkembangan penduduk Jakarta yang cukup pesat. Namun ternyata, roda modernitas itu tak bisa dikendalikan. Hidup sederhana dan bersahaja yang sebelumnya dianut oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Hal ini barangkali bagian dari reaksi masyarakat melihat perubahan fisik dari ruang hidupnya.
Dalam kondisi transisi perubahan ke arah modernitas ini, tentunya banyak hal yang bisa menjadi perhatian. Dan pusat perhatian penulis yang dicurahkannnya di dalam buku ini bukanlah aspek kebijakan para pemangku kepentingan dalam pembangunan Jakarta. Penulis justru lebih berkutat pada permasalahan mikro, seperti perjudian, pornografi, film, komik, makanan, mainan anak-anak, dan kebiasaan berbelanja warga Jakarta di tahun 1970-an.
Melalui pengalaman empiris antropologis yang didukung dengan referensi, dokumentasi dan wawancara kepada orang-orang yang mengalami kehidupan pada periode tersebut, hadirnya buku kumpulan esai ini sekarang, maka seperti seorang kakek yang menceritakan tentang kehidupan Jakarta tahun 1970-an kepada cucunya. Beragam kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di Jakarta pada 1970-an dikupas tuntas sampai dengan istilah-istilah khas pada masa itu. Cerita itu mengalir begitu saja.
Buku-buku yang membahas sejarah kota Jakarta barangkali sudah ada. Namun, buku yang secara khusus membicarakan fenomena budaya popular yang tumbuh dan berkembang di Jakarta pada kisaran 1970-an, baru Zeffry Alkatiri yang melakukannya. Seperti pengantar yang ditulisnya, dengan berbasiskan berbagai objek popular itu, penulis berharap dapat memperlihatkan suatu kesinambungan perubahan budaya, baik dalam skala cepat maupun lambat tentang kedinamikaan suatu kota yang berbasis masyarakat majemuk ini.
Melalui buku ini, penulis seakan-akan ingin mengembalikan ingatan kita terhadap muasal terbentuknya keberagaman dan modernitas di Jakarta. Dengan memahami apa yang kita makan, minum, saksikan, lakukan dan impikan di masa Jakarta tahun 1970-an, harapannya tentu saja bisa melakukan refleksi diri. Apalagi bagi warga Jakarta sendiri, mengingat Jakarta hari ini semakin ruwet, mengetahui riwayat dinamika kotanya sendiri tentu akan sangat membantu merumuskan cara hidup sehat di kota ini. Sehingga masalah-masalah yang tak kunjung terselesaikan di Jakarta, seperti banjir, macet, transportasi umum yang tak layak, bisa dipahami akar-akar penyebabnya.
Sepertinya wajar bila sebagian kalangan berpendapat bahwa sekarang Jakarta bukan milik warganya. Jakarta hari ini adalah milik sebagian orang yang berduit dan berkuasa. Karena kenyataannya, sebagian besar penduduk Jakarta yang berasal dari kalangan bawah dan menengah, cukup sulit hidup dengan nyaman di Jakarta.
Ratno Fadillah, bekerja di sebuah penerbitan di Jakarta
Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 Agustus 2010
No comments:
Post a Comment