-- Ninuk Mardiana Pambudy
SEPERTI pergelaran wayang kulit yang menjadi minatnya, Iwan Tirta (75) telah tancep kayon. Ia menutup perjalanan hidupnya, menghadap Sang Khalik pada hari Sabtu (31/7) pukul 08.35 di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta.
Indonesia kehilangan putra terbaik lagi dengan perginya sang maestro batik. Menurut asisten pribadinya, Sutisna, Iwan dirawat di rumah sakit selama 10 hari karena komplikasi tingginya gula darah, infeksi paru dan jantung, serta lima hari terakhir gagal ginjal. Selepas asar, jenazah Iwan Tirta dibawa ke TPU Karet untuk dikebumikan di makam ayah dan ibunya.
Hadir di rumah duka di Jalan Panarukan, Menteng, antara lain Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, yang ibunya bersepupu dengan ibu Iwan Tirta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Tatik Fauzi Bowo yang bertetangga dengan Iwan Tirta di Menteng.
Turut melayat sahabat dan desainer, antara lain Toeti Herati Noerhadi, Ghea S Panggabean, Harry Darsono, Fauzi Ichsan, Pia Alisyahbana, Baron Manansang, Joop Ave, Rachmat Gobel, Niniek L Karim, dan Linda Hoemar.
Nusjirwan Tirtaamidjaja, nama lengkapnya, menjadi sosok istimewa dalam perjalanan seni batik modern Indonesia. Dengan pemahaman teknis hingga ke falsafah mendalam, Iwan berhasil mengangkat batik menjadi gaya hidup kalangan atas Tanah Air dan internasional. Sumbangan tersebut terasa hingga kini.
Iwan membatik di atas berjenis sutra dan kemudian wol. Ciri khasnya, corak ukuran besar dan tegas, termasuk untuk kain perempuan. Ia memopulerkan lapisan prada keemasan sehingga batik tampil mewah dan megah. Dengan mengajak desainer Chossy Latu, Iwan mengubah batik dari kain panjang menjadi gaun indah yang praktis.
Iwan Tirta pula yang membuat batik Indonesia mendunia ketika tampil dalam majalah bergengsi National Geogprahic edisi Amerika pada akhir 1980-an. Iwan ditampilkan sebagai ikon batik Indonesia dan Okky Asokawati, kini anggota DPR, menjadi model membawakan gaun malam karya Iwan.
Iwan pula yang membuatkan kemeja batik para kepala negara Asia Pasifik peserta pertemuan APEC 1994 di Istana Bogor.
Menurut Ketua Ikatan Perancang Mode Indonesia yang pernah menjadi asisten Iwan, Sjamsidar Isa, Iwan juga memelopori batik dalam interior ketika berhasil meyakinkan hotel-hotel bintang lima di Jakarta dan Bali memakai batik saat konferensi pariwisata PATA tahun 1970-an.
Corak batik Iwan Tirta juga yang digunakan Chossy Latu dalam desain seragam awak Garuda Indonesia yang masih dipakai hingga kini. Pemahaman yang mendalam pada batik pula yang membuat Iwan tanpa kesulitan memindahkan corak batik ke dalam peralatan makan porselen dan barang perak.
Linda Amalia Sari, salah satu pendiri Rumah Pesona Kain, dan Niniek L Karim mengenang Iwan Tirta sebagai sosok yang siap membagi pengetahuannya yang luas kepada siapa saja.
Pribadi yang kaya
Iwan Tirta adalah pribadi yang kaya. Ayahnya, Mohamad Husein Tirtaamidjaja, hakim kelahiran Purwakarta, Jawa Barat. Ibunya, Ramah Saleh, berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat, pernah belajar di sekolah kedokteran STOVIA. Iwan sendiri lahir di Blora, 18 April 1935. Orangtuanya memperkenalkan Iwan pada budaya Jawa, terutama cara hidup kalangan ningrat, serta disiplin pendidikan Barat.
Banyak faktor membuat Iwan yang semula bercita-cita menjadi ahli hukum dan diplomat beralih menjadi seniman batik.
Setelah menyelesaikan sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 1958, Iwan melanjutkan pendidikan S-2-nya ke London School of Oriental & African Studies, London University (1961). Dia mendapat master of laws dari Yale University di New Haven, Connecticut, AS (1967), dan beasiswa Yayasan Adlai Stevenson di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dana hibah dari John D Rockefeller III Fund memberi kesempatan Iwan mempelajari tarian Kesunanan Surakarta. Saat itulah Iwan belajar tentang batik dalam kosmologi Jawa, konteks Indonesia, dan kaitannya dengan seni lain, seperti tari, wayang, musik, hingga ukir.
Sebelumnya, Indonesianis dari Cornell University, AS, Bennedict Anderson, yang indekos di rumah orangtua Iwan di Menteng saat sedang meneliti di Jakarta, mendorong Iwan mendokumentasi batik. Maka, lahirlah buku Batik, Pola & Tjorak-Pattern & Motif (1962, Djambatan).
Sosok yang juga memengaruhi Iwan Tirta adalah Panembahan Hardjonagoro (Go Tik Swan), empu batik dan budayawan yang diminta Presiden Soekarno membuat batik Indonesia. Iwan menyebut Hardjonagoro (meninggal 5 November 2008) sebagai gurunya.
Kecenderungannya pada kerja ilmiah membuat Iwan mendekati batik secara rasional, seperti terlihat dalam bukunya, Batik, A Play of Light and Shades (1996, Gaya Favorit Press), yang menuturkan sejarah batik Indonesia dalam konteks sosial dan budaya dengan pembabakan seperti pertunjukan wayang. Versi bahasa Indonesia dengan tambahan informasi lebih personal lahir kemudian dalam Batik, Sebuah Lakon (2009, Gaya Favorit Press).
Warisan
Meski namanya besar sebagai budayawan dan maestro batik, dari sisi bisnis Iwan tidak terlalu berhasil.
Setelah krisis ekonomi 1998, upaya mendirikan usaha bersama mitra bisnisnya kandas. Iwan pun kehilangan hak atas merek Iwan Tirta. Produk yang lahir kemudian menggunakan nama IT Private Collection. Belakangan dia mendirikan PT Pusaka Iwan Tirta dan pada 1 Desember 2010 berencana meluncurkan Yayasan Iwan Tirta yang akan mengembangkan corak batik Iwan Tirta.
Bagi Iwan, batik hanya berkembang bila dikenakan sehari-hari.
Menurut Iwan, kunci melestarikan batik adalah melalui pendidikan dan riset. Justru pada dua hal itu Iwan merasa prihatin karena pemerintah dan masyarakat masih abai meski batik Indonesia telah diakui Unicef sebagai warisan budaya dunia tak benda.
Ia sendiri telah mewujudkan keyakinan itu. Dengan bantuan Rachmat Gobel, Iwan mendokumentasi digital beragam corak batik, termasuk ciptaannya, setelah krisis ekonomi 1998.
Dimintai komentarnya, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, demi kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, diperlukan upaya asertif untuk mengembangkan batik warisan Iwan Tirta. Walau bersedia memfasilitasi, ia mengatakan, hal itu tergantung dari keluarga.
Iwan pernah mengatakan, meski tak melahirkan batik, ia akan terus memelihara dan mengasuh yang ada. ”Seperti emban,” ucapnya.
Kini, sang maestro telah tancep kayon, menemukan pelabuhan terakhir di pangkuan Sang Khalik. Tetapi, warisannya harus terus berkembang bersama Indonesia. (iya)
Sumber: Kompas, Minggu, 1 Agustus 2010
Sunday, August 01, 2010
[Buku] Membaca Muasal Nilai-Nilai Komersial di Jakarta
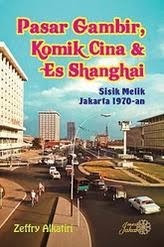 Judul buku: Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-an
Judul buku: Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-anPenulis: Zaffry Alkatiri
Penerbit: Masup Jakarta - Komunitas Bambu
Tebal: x + 190 hlm
KOTA bukan sekadar lanskap geografis. Kota adalah wajah masyarakat yang menempatinya. Keberadaan dan perkembangannya adalah representasi dari eksistensi dan pergulatan hidup masyarakatnya. Memahami sejarah sebuah kota senantiasa akan membawa kita pada pemahaman kompleksitas kehidupan dalam suatu ruang. Dari kehidupan sosial, ekonomi, bahasa, budaya, sampai tradisi lokal yang telah turun-temurun.
Buku Pasar Gambir, Komik Cina, dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970-an, mencoba merekam kehidupan warga kota Jakarta dengan segala kompleksitas dan kemajemukannya. Dengan membatasi lingkup waktu hanya sekitar tahun 1970-an, penulis rupanya ingin memotret dinamika awal modernisasi kota Jakarta.
Pada 1970-an, para pemangku kepentingan yang sangat berkepentingan atas pembangunan kota Jakarta memang berupaya membentuk identitas Jakarta. Pada 1970-an dinyatakan Jakarta tidak akan berkembang menjadi kota metropolitan seperti yang digembar-gemborkan pemerintahnya. Jakarta akan tetap menjadi sebuah perkampungan besar, dengan segala persoalannya yang rumit. Kala itu, Ali Sadikin, gubernur Jakarta, juga pernah menyatakan bahwa Jakarta kota tertutup bagi pendatang. Hal ini diungkapkannya akibat laju perkembangan penduduk Jakarta yang cukup pesat. Namun ternyata, roda modernitas itu tak bisa dikendalikan. Hidup sederhana dan bersahaja yang sebelumnya dianut oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Hal ini barangkali bagian dari reaksi masyarakat melihat perubahan fisik dari ruang hidupnya.
Dalam kondisi transisi perubahan ke arah modernitas ini, tentunya banyak hal yang bisa menjadi perhatian. Dan pusat perhatian penulis yang dicurahkannnya di dalam buku ini bukanlah aspek kebijakan para pemangku kepentingan dalam pembangunan Jakarta. Penulis justru lebih berkutat pada permasalahan mikro, seperti perjudian, pornografi, film, komik, makanan, mainan anak-anak, dan kebiasaan berbelanja warga Jakarta di tahun 1970-an.
Melalui pengalaman empiris antropologis yang didukung dengan referensi, dokumentasi dan wawancara kepada orang-orang yang mengalami kehidupan pada periode tersebut, hadirnya buku kumpulan esai ini sekarang, maka seperti seorang kakek yang menceritakan tentang kehidupan Jakarta tahun 1970-an kepada cucunya. Beragam kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di Jakarta pada 1970-an dikupas tuntas sampai dengan istilah-istilah khas pada masa itu. Cerita itu mengalir begitu saja.
Buku-buku yang membahas sejarah kota Jakarta barangkali sudah ada. Namun, buku yang secara khusus membicarakan fenomena budaya popular yang tumbuh dan berkembang di Jakarta pada kisaran 1970-an, baru Zeffry Alkatiri yang melakukannya. Seperti pengantar yang ditulisnya, dengan berbasiskan berbagai objek popular itu, penulis berharap dapat memperlihatkan suatu kesinambungan perubahan budaya, baik dalam skala cepat maupun lambat tentang kedinamikaan suatu kota yang berbasis masyarakat majemuk ini.
Melalui buku ini, penulis seakan-akan ingin mengembalikan ingatan kita terhadap muasal terbentuknya keberagaman dan modernitas di Jakarta. Dengan memahami apa yang kita makan, minum, saksikan, lakukan dan impikan di masa Jakarta tahun 1970-an, harapannya tentu saja bisa melakukan refleksi diri. Apalagi bagi warga Jakarta sendiri, mengingat Jakarta hari ini semakin ruwet, mengetahui riwayat dinamika kotanya sendiri tentu akan sangat membantu merumuskan cara hidup sehat di kota ini. Sehingga masalah-masalah yang tak kunjung terselesaikan di Jakarta, seperti banjir, macet, transportasi umum yang tak layak, bisa dipahami akar-akar penyebabnya.
Sepertinya wajar bila sebagian kalangan berpendapat bahwa sekarang Jakarta bukan milik warganya. Jakarta hari ini adalah milik sebagian orang yang berduit dan berkuasa. Karena kenyataannya, sebagian besar penduduk Jakarta yang berasal dari kalangan bawah dan menengah, cukup sulit hidup dengan nyaman di Jakarta.
Ratno Fadillah, bekerja di sebuah penerbitan di Jakarta
Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 Agustus 2010
Mengkaji Gerakan Sastra 'Horison'
-- Abdul Aziz Rasjid
TAUFIQ Ismail pernah merasa bahwa dirinya bersama puluhan anak SMA lain seangkatannya di seluruh Tanah Air telah menjadi generasi nol buku yang rabun membaca dan pincang mengarang. Istilah nol buku menerangkan pada kala itu mereka tidak mendapat tugas membaca melalui perpustakaan sekolah sehingga mereka menjadi rabun membaca. Sedangkan istilah pincang mengarang diakibatkan tidak adanya latihan mengarang dalam pelajaran di sekolah.
Keadaan generasi yang rabun membaca dan pincang mengarang itu lalu diindikasikan Taufiq Ismail sebagai sebab mendasar amburadulnya Indonesia hari ini karena dimungkinkan generasi nol buku inilah yang kini menjadi warga Indonesia terpelajar dan memegang posisi menentukan arah Indonesia di seluruh strata, baik di pemerintahan maupun swasta.
Didorong oleh keresahan pada adanya generasi nol buku itulah, lalu Taufik Ismail menggagas gerakan sastra bersama majalah Horison�di mana Taufik Ismail pernah menjadi redaktur senior dan salah satu dewan redaksi--dengan tujuan menumbuhkan budaya membaca dan menulis bagi pelajar sekolah menengah, santri pesantren, maupun mahasiswa bagi kemajuan pendidikan sastra di Indonesia. Taufik Ismail dan Horison tak main-main memang, sasaran yang dituju meliputi SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK, sampai mahasiswa se-Indonesia.
Gerakan sastra itu terdiri dari lima program, berupa 1). Sisipan Kaki Langit (SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK) dalam majalah Horison, 2). Pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra untuk guru Bahasa dan Sastra di seluruh provinsi (Februari--Oktober 2002), 3). Program Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya (SBSB), dan 5). Program Sastrawan Bicara, dan Mahasiswa Membaca (SBMM).
Sisipan Kaki Langit (SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK) dalam majalah Horison digunakan sebagai medium mengenalkan sosok dan karya sastrawan Indonesia pada siswa. Sosok, karya, proses kreatif sastrawan Indonesia lalu diulas oleh Horison dengan harapan dapat memberi influence bagi siswa untuk lebih kreatif menulis, mengambil referensi, dan lebih akrab pada karya-karya sastrawan Indonesia. Untuk mempermudah akses pengonsumsian pada siswa, majalah Horison lalu disebar secara gratis ke SMA, madrasah aliah, pesantren, dan SMK.
Di sisi lain, sisipan Kaki Langit dalam majalah Horison juga menjadi wadah bagi siswa dan guru bahasa dan sastra Indonesia untuk mengenalkan karyanya.
Siswa dapat menuliskan sajak, cerita mini, esai di mana karya siswa ini lalu ditelaah oleh Horison. Telaah yang dilakukan Horison dapat dikatakan sebagai edukasi sekaligus evaluasi agar teknik menulis siswa dapat lebih berkembang. Sedangkan guru bahasa dan sastra Indonesia sebagai eksekutor terpenting dalam lingkup pendidikan (sekolah menengah, pesantren) untuk membudayakan siswa membaca dan menulis, dalam sisipan Kaki Langit dapat berbagi pengalaman tentang metode pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah lewat kolom Pengalaman Guru.
Tiga Program lainnya, yaitu pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra untuk guru Bahasa dan Sastra di seluruh provinsi (Februari--Oktober 2002), Program Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya (SBSB), dan Program Sastrawan Bicara, Mahasiswa Membaca (SBMM) adalah ajang promosi gagasan untuk membudayakan membaca dan menulis di instansi pendidikan, dan juga perjumpaan secara langsung antara beberapa sastrawan dengan sasaran gerakan sastra.
Program-program di atas setidaknya menjelaskan bahwa tradisi membaca dan menulis bagi siswa SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK dan mahasiswa telah digalakkan. Hasil ideal juga telah didapati, yaitu adanya karya yang dihasilkan siswa SMA, madrasah aliyah, pesantren, SMK, dan mahasiswa yang kemudian dimuat dalam majalah Horison. Persoalan selanjutnya, tinggal bagaimana karya mereka selanjutnya (baik masih sebagai mahasiswa atau pelajar maupun setelah mentas sebagai mahasiswa atau pelajar) dapat diterbitkan lalu dikonsumsi masyarakat? Untuk dapat memprediksi sejauh apa peluang-peluang karya mereka dapat diterbitkan, tentu harus ditengok dahulu sistem penerbitan karya yang berjalan di Indonesia ini.
Menurut Yosi Ahmadun Herfanda dalam Kapitalisasi Sistem Produk Sastra Kota (Horison, edisi September 2004), secara umum keadaan sistem industri budaya di Indonesia terbagi menjadi dua kubu, kubu pertama adalah sistem industri market oriented yang secara jelas mengejar pengembangan modal. Sedang kubu kedua adalah sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal. Dua hal ini memili corak tersendiri, karena memang secara dasar memiliki watak yang berbeda.
Sistem industri market oriented dilihat dari wataknya yang melakukan kapitalisasi produksi untuk pengembangan modal membentuk konsekuensi logis bagi penulis, yaitu berkompromi dengan kepentingan kapitalis, dalam sistem ini karya sebagai hasil produksi pemikiran dan kekreatifan penulis memang diharuskan sesuai dengan keinginan pasar yang dipersepsikan oleh kapitalis. Dalam sistem ini, maka peluang penulis menjadi besar jika idealisasi konsep penciptaan karya yang diyakini benar untuk sementara dipinggirkan lalu tunduk pada keinginan pasar yang dipersepsikan oleh kapitalis. Dampak yang terjadi kemudian, penulis hanya akan menjadi tenaga kerja produktif, karena tujuan penulisan karya demi popularitas dan pendapatan financial reward yang relatif besar.
Pada sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal atau dapat dikatakan sebagai kegiatan penerbitan yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan modal--dalam bidang sastra Ahmadun mencontohkan Horison, Komunitas Sastra Indonesia, Forum Lingkar Pena, dan Teater Utan Kayu, konsekuensi logis bagi penulis agar karyanya dapat tersosialisasi harus sesuai dengan standar yang dipatok oleh komunitas itu. Sistem ini, secara positif memberi peluang kebebasan pada penulis untuk menuliskan idealisasinya, asal idealisasi itu harus melebihi atau sesuai dengan standar yang dipatok oleh komunitas, sedang sisi negatifnya akan melahirkan penulis-penulis yang hanya akan menjadi tenaga kerja repetitif karena tujuan penulisan sekadar menyesuaikan selera komunitas.
Dalam sistem penerbitan inilah, pekerjaan rumah gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan tradisi membaca dan menulis semacam yang dilakukan majalah Horison mendapat tantangan sebenarnya, yaitu memberitahu sejak dini pada siswa pentingnya menjadi tenaga ahli dalam bidang apa pun, lalu mewartakan tentang pentingnya cara menyiasati peluang-peluang pemasaran karya guna mempertahankan idealisasi pemikiran mereka.
Abdul Aziz Rasjid, Peneliti Beranda Budaya, tinggal di Purwokerto
Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 Agustus 2010
TAUFIQ Ismail pernah merasa bahwa dirinya bersama puluhan anak SMA lain seangkatannya di seluruh Tanah Air telah menjadi generasi nol buku yang rabun membaca dan pincang mengarang. Istilah nol buku menerangkan pada kala itu mereka tidak mendapat tugas membaca melalui perpustakaan sekolah sehingga mereka menjadi rabun membaca. Sedangkan istilah pincang mengarang diakibatkan tidak adanya latihan mengarang dalam pelajaran di sekolah.
Keadaan generasi yang rabun membaca dan pincang mengarang itu lalu diindikasikan Taufiq Ismail sebagai sebab mendasar amburadulnya Indonesia hari ini karena dimungkinkan generasi nol buku inilah yang kini menjadi warga Indonesia terpelajar dan memegang posisi menentukan arah Indonesia di seluruh strata, baik di pemerintahan maupun swasta.
Didorong oleh keresahan pada adanya generasi nol buku itulah, lalu Taufik Ismail menggagas gerakan sastra bersama majalah Horison�di mana Taufik Ismail pernah menjadi redaktur senior dan salah satu dewan redaksi--dengan tujuan menumbuhkan budaya membaca dan menulis bagi pelajar sekolah menengah, santri pesantren, maupun mahasiswa bagi kemajuan pendidikan sastra di Indonesia. Taufik Ismail dan Horison tak main-main memang, sasaran yang dituju meliputi SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK, sampai mahasiswa se-Indonesia.
Gerakan sastra itu terdiri dari lima program, berupa 1). Sisipan Kaki Langit (SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK) dalam majalah Horison, 2). Pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra untuk guru Bahasa dan Sastra di seluruh provinsi (Februari--Oktober 2002), 3). Program Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya (SBSB), dan 5). Program Sastrawan Bicara, dan Mahasiswa Membaca (SBMM).
Sisipan Kaki Langit (SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK) dalam majalah Horison digunakan sebagai medium mengenalkan sosok dan karya sastrawan Indonesia pada siswa. Sosok, karya, proses kreatif sastrawan Indonesia lalu diulas oleh Horison dengan harapan dapat memberi influence bagi siswa untuk lebih kreatif menulis, mengambil referensi, dan lebih akrab pada karya-karya sastrawan Indonesia. Untuk mempermudah akses pengonsumsian pada siswa, majalah Horison lalu disebar secara gratis ke SMA, madrasah aliah, pesantren, dan SMK.
Di sisi lain, sisipan Kaki Langit dalam majalah Horison juga menjadi wadah bagi siswa dan guru bahasa dan sastra Indonesia untuk mengenalkan karyanya.
Siswa dapat menuliskan sajak, cerita mini, esai di mana karya siswa ini lalu ditelaah oleh Horison. Telaah yang dilakukan Horison dapat dikatakan sebagai edukasi sekaligus evaluasi agar teknik menulis siswa dapat lebih berkembang. Sedangkan guru bahasa dan sastra Indonesia sebagai eksekutor terpenting dalam lingkup pendidikan (sekolah menengah, pesantren) untuk membudayakan siswa membaca dan menulis, dalam sisipan Kaki Langit dapat berbagi pengalaman tentang metode pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah lewat kolom Pengalaman Guru.
Tiga Program lainnya, yaitu pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra untuk guru Bahasa dan Sastra di seluruh provinsi (Februari--Oktober 2002), Program Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya (SBSB), dan Program Sastrawan Bicara, Mahasiswa Membaca (SBMM) adalah ajang promosi gagasan untuk membudayakan membaca dan menulis di instansi pendidikan, dan juga perjumpaan secara langsung antara beberapa sastrawan dengan sasaran gerakan sastra.
Program-program di atas setidaknya menjelaskan bahwa tradisi membaca dan menulis bagi siswa SMA, madrasah aliah, pesantren, SMK dan mahasiswa telah digalakkan. Hasil ideal juga telah didapati, yaitu adanya karya yang dihasilkan siswa SMA, madrasah aliyah, pesantren, SMK, dan mahasiswa yang kemudian dimuat dalam majalah Horison. Persoalan selanjutnya, tinggal bagaimana karya mereka selanjutnya (baik masih sebagai mahasiswa atau pelajar maupun setelah mentas sebagai mahasiswa atau pelajar) dapat diterbitkan lalu dikonsumsi masyarakat? Untuk dapat memprediksi sejauh apa peluang-peluang karya mereka dapat diterbitkan, tentu harus ditengok dahulu sistem penerbitan karya yang berjalan di Indonesia ini.
Menurut Yosi Ahmadun Herfanda dalam Kapitalisasi Sistem Produk Sastra Kota (Horison, edisi September 2004), secara umum keadaan sistem industri budaya di Indonesia terbagi menjadi dua kubu, kubu pertama adalah sistem industri market oriented yang secara jelas mengejar pengembangan modal. Sedang kubu kedua adalah sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal. Dua hal ini memili corak tersendiri, karena memang secara dasar memiliki watak yang berbeda.
Sistem industri market oriented dilihat dari wataknya yang melakukan kapitalisasi produksi untuk pengembangan modal membentuk konsekuensi logis bagi penulis, yaitu berkompromi dengan kepentingan kapitalis, dalam sistem ini karya sebagai hasil produksi pemikiran dan kekreatifan penulis memang diharuskan sesuai dengan keinginan pasar yang dipersepsikan oleh kapitalis. Dalam sistem ini, maka peluang penulis menjadi besar jika idealisasi konsep penciptaan karya yang diyakini benar untuk sementara dipinggirkan lalu tunduk pada keinginan pasar yang dipersepsikan oleh kapitalis. Dampak yang terjadi kemudian, penulis hanya akan menjadi tenaga kerja produktif, karena tujuan penulisan karya demi popularitas dan pendapatan financial reward yang relatif besar.
Pada sistem industri yang tidak mengejar pengembangan modal atau dapat dikatakan sebagai kegiatan penerbitan yang tidak dimaksudkan untuk pengembangan modal--dalam bidang sastra Ahmadun mencontohkan Horison, Komunitas Sastra Indonesia, Forum Lingkar Pena, dan Teater Utan Kayu, konsekuensi logis bagi penulis agar karyanya dapat tersosialisasi harus sesuai dengan standar yang dipatok oleh komunitas itu. Sistem ini, secara positif memberi peluang kebebasan pada penulis untuk menuliskan idealisasinya, asal idealisasi itu harus melebihi atau sesuai dengan standar yang dipatok oleh komunitas, sedang sisi negatifnya akan melahirkan penulis-penulis yang hanya akan menjadi tenaga kerja repetitif karena tujuan penulisan sekadar menyesuaikan selera komunitas.
Dalam sistem penerbitan inilah, pekerjaan rumah gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan tradisi membaca dan menulis semacam yang dilakukan majalah Horison mendapat tantangan sebenarnya, yaitu memberitahu sejak dini pada siswa pentingnya menjadi tenaga ahli dalam bidang apa pun, lalu mewartakan tentang pentingnya cara menyiasati peluang-peluang pemasaran karya guna mempertahankan idealisasi pemikiran mereka.
Abdul Aziz Rasjid, Peneliti Beranda Budaya, tinggal di Purwokerto
Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 Agustus 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)